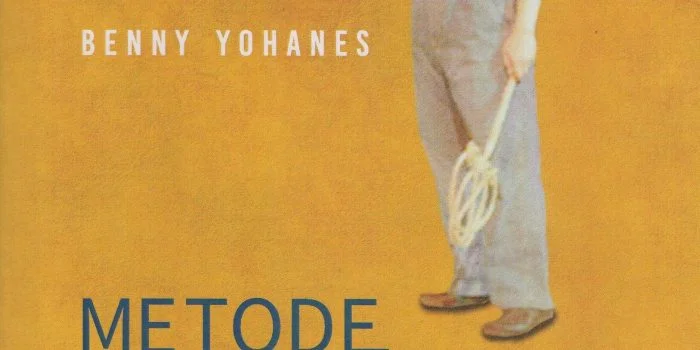Karena itu, setidaknya, akan ditemui dua problem penting yang cukup menantang ketika membaca buku ini. Pertama, problem paradigmatik. Sebagai praktisi dan akademisi teater, ternyata BenJon lebih memilih logika dan cara ungkap sebagaimana sistematika yang berlangsung dalam cara berpikir filsafat. Ia bisa memberikan pemaparan tentang idealisme dan impresi secara bersamaan. Atau, wacana tradisi yang serta merta dibenturkan dengan poststrukturalisme tapi menggunakan perspektif analisis modern. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Salah satu disiplin ilmu dalam pendidikan formal yang ditempuh BenJon adalah magister filsafat di Universitas Indonesia. Karenanya, jika menghendaki pemaparan yang sederhana, terang, dan tidak memutar dalam pembacaan buku ini, akan menjadi sesuatu yang mustahil bisa didapat.
Kedua, problem kognitif. Buku ini secara tegas diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki perhatian dan kapasitas baik terhadap kajian serta penulisan kritik seni, khususnya teater. Karena itu, pembaca awam teori dan pengalaman teater, tampaknya perlu mengagendakan pembacaan terhadap buku ini sebagai tahapan lanjut setelah beberapa literatur dasar menjadi bekal dan pemahaman secara utuh. Sebab, dalam buku ini, BenJon tidak memberikan peluang kilas balik atas fakta dan peristiwa elementer yang berlangsung secara masif di depan publik teater kebanyakan.
Termasuk ketika memecah periodisasi tumbuhkembangnya teater modern di Indonesia, BenJon memulai dan mengakhirinya hanya sejak tahun 1970-an sampai 1990-an saja. Artinya, masa sebelum dan sesudah tahun itu tidak begitu menjadi perhatian penting bagi BenJon. Pertimbangan tersebut, boleh jadi, merujuk pada data dan fakta yang dianggapnya cukup fenomenal dan dapat mewakili karakter serta gagasan setiap kelompok sejalan dengan masa yang menjadi saksi atas keberlangsungan teater modern Indonesia.
Baca Juga:Seniman dan Jual-Gadai KemiskinanSurat Terbuka untuk Rakyat Amerika, Saat Rusia Merayakan Kemenangan Perang Dunia II Atas Nazi
Tetapi, menurut saya, ini menjadi celah penting bagi pembaca untuk melakukan kritik balik terhadap keputusan BenJon melakukan pembatasan historiografi teater modern Indonesia itu. Agar publik secara umum, tidak disuguhi sejarah teater modern Indonesia secara parsial dan fragmentatif.
Sekadar contoh, di tahun 1950-an—sebelum Rendra mendirikan Bengkel Teater, sudah berdiri Teater Muslim di Yogyakarta yang digawangi Mohamad Diponegoro. Di sana jugalah Arifin C Noer menimba ilmu. Teater Muslim telah memberikan warna dan menawarkan sebentuk estetika khas yang kini hampir tidak lagi menjadi inspirasi dan kesadaran sikap para pelaku teater yang mengandaikan dirinya sebagai muslim. Mungkin, hari ini, tinggal Sanggar Salahuddin UGM dan Teater ESKA UIN Sunan Kalijaga saja yang masih cukup konsisten untuk menapak jejak yang pernah ditempuh Teater Muslim. Tentu saja, pilihan ini tidak begitu saja menjadikan kelompok ini sebagai mimesis atau epigon secara mentah atas gagasan dan praktik kelompok yang mereka jadikan rujukan itu.